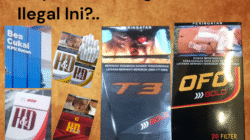Merdeka atau Penjajahan Model Baru?
Daulatkepri.com] Merdeka, Tapi untuk Siapa?
“Merdeka… Merdeka… Merdeka!”
Dulu pekik itu membuat bulu kuduk berdiri.
Hari ini, entah kenapa, justru bikin perut mual.
Setiap tahun, 17 Agustus diperingati dengan gegap gempita. Namun, di balik parade, upacara bendera, dan lomba rakyat, muncul pertanyaan getir: apakah kemerdekaan benar-benar dirasakan rakyat, atau justru berubah wajah menjadi bentuk penjajahan baru oleh bangsa sendiri?
Laut: Dari Halaman Bersama ke Wilayah Terbatas
Sebelum 1945, laut Nusantara adalah jalur perdagangan bebas. Kesultanan Riau, Lingga, Bugis, hingga Makassar berdagang lintas samudra tanpa batas formal.
Adat dan mufakat jadi aturan utama. Pedagang asing—Belanda, Portugis, Inggris—datang membeli dan menukar. Mereka kuat, tetapi tidak berkuasa penuh.
Hari ini, setelah republik lahir, laut tak lagi bebas. Garis batas ditarik. Pajak ditetapkan. Izin diperketat. Yang membayar, bisa jalan. Yang melawan, terancam hukum.
Penjajahan Baru: Regulasi sebagai Senjata
Kalau dulu penjajah datang dengan kapal perang, kini mereka cukup duduk di balik meja. Cukup tanda tangan.
Aturan dibuat, pasal samar disisipkan, celah emas dibuka. Pejabat ditempatkan di posisi strategis. Masyarakat kehilangan ruang hidup, sementara negara menegakkan hukum untuk kepentingan pemodal.
“Kalau mau mencuri, buat aturan dulu,” begitu ungkapan sinis yang berkembang di masyarakat.
Batam: Laboratorium Penjajahan Dalam Negeri
Batam sering dijadikan contoh modernisasi Indonesia. Dengan label free trade zone, wilayah ini digadang-gadang bisa menjadi Singapura baru.
Namun dari dalam, cerita berbeda. Masyarakat tempatan kerap merasa jadi tamu di tanah sendiri. Banyak yang harus membayar iuran bahkan untuk lahan warisan keluarga.
BP Batam, badan superpower di bawah presiden, menguasai penuh lahan dan pelabuhan. Pemerintah kota? Lebih sering hanya penonton.
Nama-nama pengusaha dan mafia lokal pun muncul: dari Akim, Bobie Jayanto, hingga inisial pemodal besar seperti AH atau DC. Skemanya mirip oligarki di Jakarta, hanya saja dalam versi pulau.
Reklamasi, Investasi, dan Lingkungan yang Digadaikan
Pantai ditimbun. Mangrove dibabat. Pulau kecil tergerus abrasi. Nelayan kehilangan mata pencaharian. Semua atas nama investasi.
Contoh paling nyata adalah proyek revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar. Nilai miliaran rupiah digelontorkan. Spesifikasi 12 meter kedalaman ditargetkan. Nyatanya, pelabuhan dangkal, kapal besar tak bisa masuk. Audit berjalan, kasus diproses, tapi hasilnya macet.
Warisan Melayu yang Digusur
Kasus Hotel Purajaya milik keluarga tokoh Melayu, Megat Rurry Afriansyah, jadi sorotan. Bangunan diratakan tanpa dasar hukum jelas. Rurry melapor ke polisi, ke DPR, hingga Polda. Semua berhenti di meja birokrasi. Ironisnya, ayah Rurry adalah salah satu tokoh yang dulu berperan dalam pembentukan BP Batam.
Pulau Penyengat jantung bahasa Melayu dan akar bahasa Indonesia pun terancam. Gurindam 12, warisan Raja Ali Haji, kini berada di pusaran komersialisasi.
Belum selesai, proyek Rempang Eco City memicu bentrokan. Ribuan masyarakat harus direlokasi demi kepentingan investasi. Gas di Natuna pun terus dieksploitasi.
Hukum Tegak, Tapi untuk Pemodal
Di lapangan, masyarakat berulang kali melihat hukum hanya berpihak pada pemilik modal. Kasus-kasus besar macet, audit BPK lambat, dan proses DPR sekadar formalitas.
Polisi, jaksa, hingga pejabat daerah sering dituding sudah “disirami”. Entah persepsi atau realita, tapi bukti di lapangan sulit dibantah.
Lebih Licin dari Penjajah Lama
Jika dulu musuh datang dengan seragam asing dan kapal perang, kini penjajah datang dengan batik resmi, jas rapi, bahkan peci di kepala. Mereka berbicara bahasa Indonesia, menandatangani regulasi, dan berbagi keuntungan dengan investor.
Lebih licin. Lebih halus. Lebih sadis.
Harapan: Tipis Tapi Masih Ada
Meski gelap, titik cahaya belum padam. Masih ada pejabat yang jujur, LSM yang konsisten, jurnalis yang berani. Masih ada juga mekanisme internasional: dari New York hingga Den Haag, dunia hanya sejauh satu klik.
Ironi 17 Agustus
Hari kemerdekaan seharusnya menjadi hari kebanggaan. Namun, bagi sebagian masyarakat, 17 Agustus justru mengingatkan bahwa penjajahan belum benar-benar usai.
Musuh hanya berganti wajah—dari kolonial asing menjadi elit dalam negeri.
Merdeka dari siapa? Untuk siapa?
Pertanyaan itu semakin nyaring.
Dan masyarakat Melayu, seperti sejarah panjangnya, bisa sabar. Bisa juga tidak.
Jika suara rakyat terus diabaikan, jangan salahkan bila api perlawanan kembali menyala.
Penulis: Monica Nathan