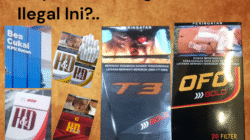Warisan Besar, Luka yang Dalam
Daulatkepri.Com] Kepulauan Riau (Kepri) kerap disebut sebagai tanah asal bahasa persatuan Indonesia. Dari tanah ini pula lahir karya sastra besar Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. Pulau Penyengat, sejarah perlawanan, hingga jejak peradaban Melayu adalah pusaka agung yang tak ternilai.
Namun, hari ini, marwah itu terasa kian hilang. Ia tak lagi dijunjung, melainkan ditukar dengan kontrak, dilelang dalam rapat-rapat penuh angka, dan diperdagangkan atas nama investasi.
Di tanah yang seharusnya menjunjung martabat Melayu, gema gurindam berganti dengan dentuman mesin, kepentingan birokrat, dan kepungan proyek besar.
 Gurindam 12: Simbol yang Diperjualbelikan
Gurindam 12: Simbol yang Diperjualbelikan
Pemerintah berencana melelang lahan Taman Gurindam 12, hanya seluas 7.500 meter persegi. Secara angka mungkin tampak kecil, namun bagi masyarakat, persoalannya bukan soal luas melainkan soal nilai.
Investor disebut ingin membangun restoran dan area parkir. Pemerintah mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi Gurindam 12 adalah pusaka, bukan kios sewaan. Ia simbol budaya, martabat, dan sejarah.
“Ketika pusaka diperlakukan seperti properti, harga diri ikut tergadai di bawah meja,” begitu keluh banyak warga.
 Purajaya: Dari Ikon Jadi Puing
Purajaya: Dari Ikon Jadi Puing
Batam pernah memiliki Purajaya, sebuah hotel yang dibangun keluarga bangsawan dan menjadi ikon peradaban Melayu di kota industri ini.
Namun kini, Purajaya hanya tinggal kenangan. Bangunan bersejarah itu dirobohkan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia dihancurkan seakan tak memiliki nilai, dilindas oleh kepentingan.
Bagi banyak orang, perobohan itu bukan sekadar hilangnya sebuah bangunan, melainkan simbol runtuhnya marwah Melayu.
 Rempang: Leluhur yang Dihapus dari Peta
Rempang: Leluhur yang Dihapus dari Peta
Kasus Rempang lebih pahit. Sebanyak 7.572 hektare tanah dialokasikan untuk proyek Eco-City. Artinya, 16 kampung tua Melayu dipaksa menghilang dari peta.
Perlawanan rakyat dibalas dengan gas air mata. Warga yang bertahan dicap pengganggu. Anak-anak menangis, ibu-ibu terpaksa mengungsi, para lelaki menghadapi aparat.
Melayu yang sudah berabad-abad hidup di tanah itu dipaksa angkat kaki, meninggalkan pusaka nenek moyang demi proyek besar yang dikemas dengan label pembangunan.
 Teluk Tering: Izin Hantu, Pancang Menikam
Teluk Tering: Izin Hantu, Pancang Menikam
Di Teluk Tering, fenomenanya lain lagi. Warga menyebut adanya “izin hantu”—dokumen yang tak pernah terlihat, tapi bekerja dengan nyata.
Tiba-tiba pancang-pancang baja berdiri di tengah laut, menancap di wilayah tangkapan nelayan. Hari ini pemerintah menyegel, besok diam-diam kembali dibuka.
Pola seperti ini menimbulkan luka mendalam. Nelayan kehilangan sumber hidup, sementara birokrasi bermain mata dengan kepentingan.
 Mangrove: Benteng yang Ditebang
Mangrove: Benteng yang Ditebang
Mangrove bagi masyarakat pesisir bukan sekadar tumbuhan. Ia benteng alami dari abrasi, penyerap karbon, sekaligus lumbung nafkah.
Namun benteng itu terus ditebang untuk reklamasi, tambang, dan kepentingan bisnis jangka pendek. Dampaknya, banjir semakin sering terjadi, penyakit merebak, dan ekonomi kecil rakyat pesisir runtuh bersama ekosistem.
Bintan, Lingga, Natuna: Kaya, Tapi Bukan untuk Rakyat
Pulau-pulau besar lain di Kepri juga mengalami pola serupa.
Bintan dan Lingga: Gunung dikeruk bauksitnya hingga jadi cekungan. Hutan habis digantikan lubang tambang.
Natuna: Gas alam melimpah, nilainya miliaran dolar. Namun nelayan setempat tetap kesulitan membeli solar, antre panjang di SPBU, dan hidup dalam keterbatasan.
Kekayaan alam memang besar, tapi rakyat tempatan selalu menjadi penonton.
 Pola yang Terulang: Pusaka Jadi Komoditas
Pola yang Terulang: Pusaka Jadi Komoditas
Apapun kasusnya Gurindam 12, Purajaya, Rempang, Teluk Tering, hingga tambang bauksit dan gas alam—pola yang terlihat selalu sama:
Pusaka dijadikan komoditas.
Tanah leluhur disulap jadi proyek.
Alam dijadikan ladang uang.
Dan rakyat? Selalu berada di pinggir panggung.
Penjajahan Model Baru
Apa yang terjadi di Kepri hari ini bukanlah kolonialisme Belanda atau Portugis yang dulu. Ini bentuk penjajahan baru.
Berbaju investasi, berlabel pembangunan, dan disahkan dengan tanda tangan pejabat. Kolonialisme kini tak lagi membawa senjata, melainkan membawa dokumen kerja sama, rencana proyek, dan janji pertumbuhan ekonomi.
Seruan: Menjaga Marwah, Merebut Martabat
Menjelang hari lahir Kepri ke-23, suara perlawanan mulai menggema. Megat Rurry Afriansyah, Panglima Utama Majelis Rakyat Kepri, menyerukan kepada seluruh masyarakat Melayu untuk bersiap diri.
“Dari nelayan, pesisir, pulau-pulau, hingga kota-kota di seluruh Kepri, mari kita berdiri bersama. Menjaga marwah, menuntut hak, dan merebut masa depan,” tegasnya.
Akhir Kata
Kepri hari ini adalah cermin: warisan agung tapi marwahnya diperdagangkan. Sumber daya besar, tapi rakyatnya tetap hidup sengsara.
Melayu tak akan terus diam. Bangkitnya semangat perlawanan bukan sekadar mempertahankan tanah atau alam, tetapi juga merebut kembali martabat dan harga diri.
Selamat ulang tahun ke-23, Kepulauan Riau. Hadiah terbaik bukan kue, bukan pesta, melainkan perjuangan rakyat untuk menolak siapa saja yang menukar marwah dengan keserakahan.
Profil Penulis:
Monica Nathan, konsultan teknologi informasi. Hidup di dunia modern, tapi hatinya selalu kembali pada akar: Melayu dan Indonesia.