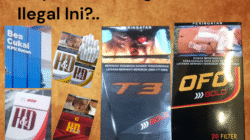Daulatkepri.Com] Hari ini, pantun seolah menjadi “alat wajib” dalam setiap acara resmi. Dari menteri di Jakarta hingga camat di pelosok desa, dari panggung hiburan sampai forum internasional, pantun dibacakan dengan penuh gaya. Dua baris awal bikin tersenyum, dua baris akhir memberi pesan yang mengikat.
Tetapi di balik kemeriahan itu, ada ironi besar: pantun yang lahir dari marwah Melayu di Kepulauan Riau (Kepri), kini mulai kehilangan wibawanya. Ia bukan lagi diperlakukan sebagai nasihat bijak atau diplomasi budaya, melainkan sekadar tempelan seremonial. Lebih buruk lagi, marwah Melayubyang jadi jiwa pantun itu sendiri pelan-pelan dirusak oleh para penjilat kekuasaan dan mafia kepentingan yang menjadikan budaya hanya komoditas dagangan.
Dari Penyengat ke Panggung Dunia
Pantun bukan datang entah dari mana. Ia lahir di pesisir Melayu, tumbuh di Kepulauan Riau, dan mencapai kematangan di Pulau Penyengat. Dari sanalah Raja Ali Haji menulis Gurindam Dua Belas, merumuskan tata bahasa Melayu, hingga meletakkan dasar yang kemudian melahirkan Bahasa Indonesia.
 Dari Kepri, pantun menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke Semenanjung Malaya. Pada 2020, UNESCO mengakuinya sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity melalui pengajuan bersama Indonesia dan Malaysia. Dunia pun memberi hormat pada pantun.
Dari Kepri, pantun menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke Semenanjung Malaya. Pada 2020, UNESCO mengakuinya sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity melalui pengajuan bersama Indonesia dan Malaysia. Dunia pun memberi hormat pada pantun.
Namun anehnya, di kampung kelahirannya sendiri, pantun sering dianggap hiburan ringan. Sementara budaya yang melahirkannya, yakni marwah Melayu, justru makin terpinggirkan oleh mafia lahan, penguasa yang tak peduli, dan elit lokal yang lebih sibuk menjilat kekuasaan pusat.
 Pantun Dato Megat Rurry: Tegas Menjaga Marwah
Pantun Dato Megat Rurry: Tegas Menjaga Marwah
Dalam peringatan 23 tahun Provinsi Kepulauan Riau, budayawan Dato Megat (DM) Rurry Afriansyah menyampaikan pantun yang menusuk kesadaran:
Untuk apa kami bersuara
Untuk tegakkan marwah Melayu
Pantun ini adalah tamparan bagi penguasa. Ia mengingatkan bahwa Melayu ramah, tetapi tidak berarti lemah. Bahwa marwah bukan untuk diperdagangkan. Bahwa Melayu lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan.
Pesannya sederhana tapi keras: Melayu adalah tuan rumah yang ramah, tapi bukan budak di tanah sendiri.
Budaya Dijual, Marwah Diperdagangkan
Sejak pemekaran tahun 2002, Kepri digadang-gadang sebagai provinsi strategis: pusat perdagangan, industri, pariwisata, dan investasi. Semua benar adanya. Tapi ada yang luput: identitas Melayu yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan, justru dipinggirkan.
Di meja rapat pejabat, pantun hanya jadi bumbu basa-basi. Di panggung politik, pantun jadi gimmick untuk meraih simpati. Di balik itu semua, mafia tanah, mafia proyek, dan elit yang menjilat terus menggerus akar budaya.
Marwah Melayu yang dulu tegak sebagai penanda harga diri kini sering ditukar dengan kontrak investasi, dijual dalam izin tambang, atau diperdagangkan lewat proyek reklamasi.

Suara dari Kepri untuk Indonesia
Pantun DM. Rurry adalah suara perlawanan dari Kepri. Ia bukan sekadar rangkaian rima, tetapi pernyataan sikap: Melayu sejati duduk berunding menyelesaikan masalah, bukan menjilat demi jabatan. Melayu sejati berpegang pada marwah, bukan menjualnya demi keuntungan sesaat.
Pesan ini penting bukan hanya untuk Kepri, tapi untuk Indonesia. Karena dari tanah ini lahir bahasa persatuan. Dari tanah ini pula dunia mengenal pantun sebagai diplomasi luhur. Menghormati pantun berarti menjaga akar Indonesia sendiri.
Penutup: Haramkan Penjilat dan Mafia
Di ulang tahun ke-23 Provinsi Kepulauan Riau, pantun kembali mengingatkan kita bahwa budaya bukan aksesori. Ia adalah identitas, sekaligus benteng moral.
Pantun bukan sekadar kata berima. Ia adalah seruan.
Melayu bukan sekadar etnis. Ia adalah marwah.
Dan marwah tidak boleh ditukar dengan kursi jabatan, proyek investasi, atau kepentingan mafia. Karena sekali marwah dilepas, bangsa ini akan kehilangan akarnya.
Seperti kata pepatah Melayu: Biar mati berputih tulang, jangan hidup menanggung malu.